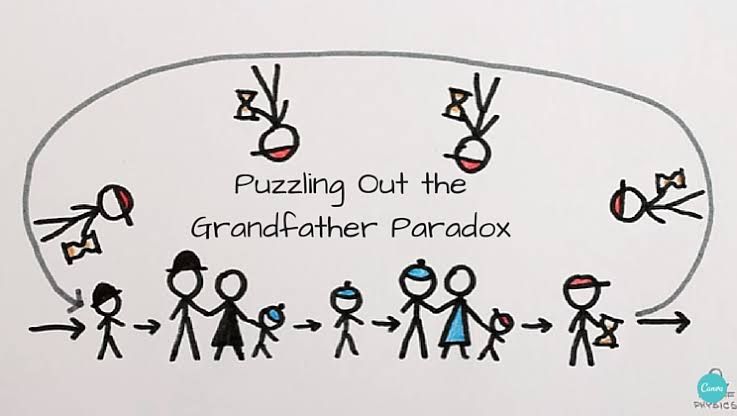Hari Raya dan Sebuah Siklus Paradoks
Setelah vakum selama dua tahun terakhir, suasana mudik lebaran akhirnya kembali hadir. Bukan hanya dari sisi menyenangkan, tapi juga sisi membingungkannya.
Untuk sisi menyenangkan, semua tentu sudah tahu, dan bisa jadi sepakat. Ada THR, menikmati hidangan lebaran, dan suasana kebersamaan yang kental.
Semua itu bahkan menyatu dengan sangat cair, meski dalam satu keluarga besar, kadang ada yang berbeda keyakinan. Satu hal yang biasa membuat momen hari raya keagamaan (khususnya di Indonesia) selalu spesial.
Di luar mereka yang berpemikiran cenderung ekstrim, saling memberi ucapan selamat saat hari raya datang sebenarnya sudah jadi tradisi sejak dulu. Bahkan, ada juga yang saling mengirim hadiah, misalnya lontong opor saat Lebaran, angpao saat Imlek, dan kue saat Natal.
Semua terasa cair, seperti dalam kehidupan sehari-hari. Keren kan?
Tapi, hari raya kadang menampilkan sebuah paradoks yang cukup membingungkan, khususnya jika dalam satu keluarga besar, ternyata ada persaingan terselubung.
Sebagai contoh, kebersamaan dalam hari raya kadang jadi satu arena unjuk gigi sebuah keluarga. Dari pakaian baru, prestasi pribadi sampai anak cucu, semua dipamerkan sampai tuntas, bahkan kadang dijadikan amunisi untuk "menembak" dengan sekuel pertanyaan "kapan" yang tersohor itu.
Fenomena ini menjadi sebuah siklus paradoks yang terus berputar, tanpa tahu kapan ujungnya. Dari generasi ke generasi selalu saja ada.
Jika berlanjut ke tahun berikutnya, apa yang ditampilkan mungkin akan lebih baik, karena ada kesan tersisa dari tahun lalu. Masalahnya, jika "pamer" terlanjur jadi titik fokus acara, ini justru akan merusak kebersamaan.
Alhasil, momen pertemuan keluarga besar hanya jadi ajang saling intip kekuatan satu keluarga. Kebersamaan pun hanya akan jadi kata kunci untuk pencitraan, meski dialah yang seharusnya jadi satu esensi.